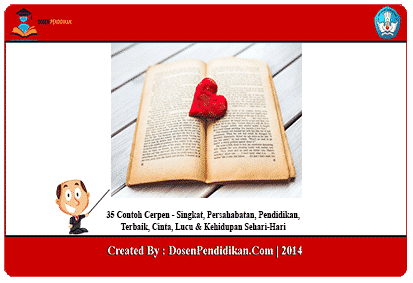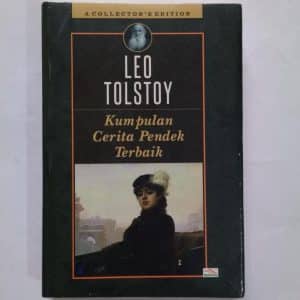35 Contoh Cerpen – Singkat, Persahabatan, Pendidikan, Terbaik, Cinta, Lucu & Kehidupan Sehari-Hari – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Contoh Cerpen yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, cara membuat, determinasi tumbuhan dan contoh, nah agar lebih dapat memahami dan mengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.
Oleh karena itu untuk pertama-tama kita membahas pengertian cerpen, cerpen adalah cerita yang wujudnya fisiknya berbentuk pendek. Untuk dapat kita mengetahui lebih jelas mari kita lihat penjelasan cerpen karna dalam pengertian cerpen serasa masih belum begitu jelas, nah untuk lebih jelasnya simak dibawah ini.
Untuk penjelasan cerpen yakni ukuran panjang-pendeknya suatu cerita memang relative, akan tetapi pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepeuluh menit atau setengah jam. Untuk jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata.
Olah karena itu, cerita pendek sering diungkapkan sebagai cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek pada umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya pun terbatas. Untuk jalan ceritanya pun sederhana dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Cerpen Adalah
Contoh Cerpen
Berikut ini terdapat beberapa contoh cerpen, terdiri atas:
1. Contoh Cerpen Terbaik
Terdiri atas:
Piknik
Cerpen Agus Noor
Para pelancong mengunjungi kota kami untuk menyaksikan kepedihan. Mereka datang untuk menonton kota kami yang hancur. Kemunculan para pelancong itu membuat kesibukan tersendiri di kota kami. Biasanya kami duduk-duduk di gerbang kota menandangi para pelancong yang selalu muncul berombongan mengendarai kuda, keledai, unta, atau permadani terbang dan juga kuda sembrani. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Dari negeri-negeri jauh yang gemerlapan.
Di bawah langit senja yang kemerahan kedatangan mereka selalu terlihat bagaikan siluet iring-iringan kafilah melintasi gurun perbatasan, membawa bermacam perbekalan piknik. Berkarung-karung gandum yang diangkut gerobak pedati, daging asap yang digantungkan di punuk unta terlihat bergoyang-goyang, roti kering yang disimpan dalam kaleng, botol-botol cuka dan saus, biskuit dan telor asin, rendang dalam rantang—juga berdus-dus mi instan yang kadang mereka bagikan pada kami.
Penampilan para pelancong yang selalu riang membuat kami sedikit merasa terhibur. Kami menduga, para pelancong itu sepertinya telah bosan dengan hidup mereka yang sudah terlampau bahagia. Hidup yang selalu dipenuhi kebahagiaan ternyata bisa membosankan juga. Mungkin para pelancong itu tak tahu lagi bagaimana caranya menikmati hidup yang nyaman tenteram tanpa kecemasan di tempat asal mereka. Karena itulah mereka ramai-ramai piknik ke kota kami: menyaksikan bagaimana perlahan-lahan kota kami menjadi debu. Kami menyukai cara mereka tertawa, saat mereka begitu gembira membangun tenda-tenda dan mengeluarkan perbekalan, lalu berfoto ramai-ramai di antara reruntuhan puing-puing kota kami. Kami seperti menyaksikan rombongan sirkus yang datang untuk menghibur kami.
Kadang mereka mengajak kami berfoto. Dan kami harus tampak menyedihkan dalam foto-foto mereka. Karena memang untuk itulah mereka mengajak kami berfoto bersama. Mereka tak suka bila kami terlihat tak menderita. Mereka menyukai wajah kami yang keruh dengan kesedihan. Mata kami yang murung dan sayu. Sementara mereka sembari berdiri dengan latar belakang puing-puing reruntuhan kota— berpose penuh gaya tersenyum saling peluk atau merentangkan tangan lebar-lebar. Mereka segera mencetak foto-foto itu, dan mengirimkannya dengan merpati-merpati pos ke alamat kerabat mereka yang belum sempat mengunjungi kota kami.
Belakangan kami pun tahu, kalau foto-foto itu kemudian dibuat kartu pos dan diperjualbelikan hingga ke negeri-negeri dongeng terjauh yang ada di balik pelangi. Pada kartu pos yang dikirimkannya itu, para pelancong yang sudah mengunjungi kota kami selalu menuliskan kalimat-kalimat penuh ketakjuban yang menyatakan betapa terpesonanya mereka saat menyaksikan kota kami perlahan-lahan runtuh dan lenyap. Mereka begitu gembira ketika melihat tanah yang tiba-tiba bergetar. Bagai ada naga menggeliat di ceruk bumi—atau seperti ketika kau merasakan kereta bawah tanah melintas menggemuruh di bawah kakimu. Betapa menggetarkan melihat pohon- pohon bertumbangan dan rumah-rumah rubuh menjadi abu. Membuat hidup para pelancong yang selalu bahagia itu menjadi lengkap, karena bisa menyaksikan segala sesuatu sirna begitu saja.
Bagi para pelancong itu, kota kami adalah kota paling menakjubkan yang pernah mereka saksikan. Mereka telah berkelana ke sudut-sudut dunia, menyaksikan beragam keajaiban di tiap kota. Mereka telah menyaksikan menara-menara gantung yang dibuat dari balok-balok es abadi, candi-candi megah yang disusun serupa tiara; menyaksikan seekor ayam emas bertengger di atas katedral tua sebuah kota yang selalu berkokok setiap pagi. Mereka juga telah melihat kota dengan kanal-kanal yang dialiri cahaya kebiru-biruan. Kepada kami para pelancong itu juga bercerita perihal kota kuno yang berdiri di atas danau bening, dengan rumah-rumah yang beranda- berandanya saling bertumpukan, dan jalan-jalannya yang menyusur dinding-dinding menghadap air, hingga menyerupai kota yang dibangun di atas cermin; kota dengan jalan layang menyerupai jejalin benang laba-laba; sebuah kota yang menyerupai benteng di ujung sebuah teluk, dengan jendela-jendela dan pintu-pintu yang selalu tertutup menyerupai gelapanggur dan hanya bisadilihat ketika senja kala. Bahkan mereka bersumpah telah mendatangi kota yang hanya bisa ditemui dalam imajinasi seorang penyair. Tapi kota kami, menurut mereka, adalah kota paling ajaib yang pernah mereka kunjungi.
Para pelancong menyukai kota kami karena kota kami dibangun untuk menanti keruntuhan. Banyak kota dibangun dengan gagasan untuk sebuah keabadian, tetapi tidak dengan kota kami. Kota kami berdiri di atas lempengan bumi yang selalu bergeser. Kau bisa membayangkan gerumbul awan yang selalu bergerak dan bertabrakan, seperti itulah tanah di mana kota kami berdiri. Membuat semua bangunan di kota kami jadi terlihat selalu berubah letaknya. Barisan pepohonan seakan berjalan pelan. Lorong-lorong, jalanan, dan sungai selalu meliuk-liuk. Dan ketika sewaktu-waktu tanah terguncang, bangunan dan pepohonan di kota kami saling bertubrukan, rubuh dan runtuh menjadi debu serupa istana pasir yang sering kau buat di pinggir pantai ketika kau berlibur menikmati laut.
Rupanya itulah pemandangan paling menakjubkan yang membuat para pelancong itu terpesona. Para pelancong itu segera menghambur berlarian menuju bagian kota kami yang runtuh, begitu mendengar kabar ada bagian kota kami yang tergoncang porak- poranda. Dengan handycam mereka merekam detik-detik keruntuhan itu. Mereka terpesona mendengar jerit ketakutan orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri, gemeretak tembok-tembok retak, suara menggemuruh yang merayap dalam tanah. Itulah detik-detik paling menakjubkan bagi para pelancong yang berkunjung ke kota kami; seolah semua itu atraksi paling spektakuler yang beruntung bisa mereka saksikan dalam hidup mereka yang terlampau bahagia. Lalu mereka memotret mayat- mayat yang tertimbun balok-balok dan batu bata. Mengais reruntuhan untuk menemukan barang-barang berharga yang bisa mereka simpan sebagai kenangan.
Saat malam tiba, dan bintang- bintang terasa lebih jauh di langit hitam, para pelancong itu bergerombol berdiang di seputar api unggun sembari berbagi cerita. Memetik kecapi dan bernyanyi. Atau rebahan di dalam tenda sembari memainkan harmonika. Dari kejauhan kami menyaksikan mereka, merasa sedikit terhibur dan tak terlalu merasa kesepian. Bagaimanapun kami mesti berterima kasih karena para pelancong itu mau berkunjung ke kota kami. Mereka membuat kami semakin mencintai kota kami. Membuat kami tak hendak pergi mengungsi dari kota kami. Karena bila para pelancong itu menganggap kota kami adalah kota yang penuh keajaiban, kenapa kami mesti menganggap apa yang terjadi di kota kami ini sebagai malapetaka atau bencana?
Seperti yang sering dikatakan para pelancong itu pada kami, setiap kota memang memiliki jiwa. Itulah yang membuat setiap kota tumbuh dengan keunikannya sendiri- sendiri. Membuat setiap kota memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Keajaiban tersendiri. Setiap kota terdiri dari gedung- gedung, sungai-sungai, kabut dan cahaya serta jiwa para penghuninya; yang mencintai dan mau menerima kota itu menjadi bagian dirinya. Kami sering mendengar kota-kota yang lenyap dari peradaban, runtuh tertimbun waktu. Semua itu terjadi bukan karena semata-mata seluruh bangunan kota itu hancur, tetapi lebih karena kota itu tak lagi hidup dalam jiwa penghuninya. Kami tak ingin kota kami lenyap, meski sebagian demi sebagian dari kota kami perlahan- lahan runtuh menjadi debu. Karena itulah kami selalu membangun kembali bagian- bagian kota kami yang runtuh. Kami mendirikan kembali rumah-rumah, jembatan, sekolah, tower dan menara, rumah sakit-rumah sakit, menanam kembali pohon- pohon, hingga di bekas reruntuhan itu kembali berdiri bagian kota kami yang hancur. Kota kami bagaikan selalu muncul kembali dari reruntuhan, seperti burung phoenix yang hidup kembali dari tumpukan abu tubuhnya.
Kesibukan kami membangun kembali bagian kota yang runtuh menjadi tontonan juga bagi para pelancong itu. Sembari menaiki pedati, para pelancong itu berkeliling kota menyaksikan kami yang tengah sibuk menata reruntuhan. Mereka tersenyum dan melambai ke arah kami, seakan dengan begitu mereka telah menunjukkan simpati pada kami. Sesekali para pelancong itu berhenti, membagikan sekerat biskuit, sepotong dendeng, sebotol minuman, atau sesendok madu, kemudian kembali pergi untuk melihat-lihat bagian lain kota kami yang masih bergerak bertabrakan dan hancur. Kemudian para pelancong itu pergi dengan bermacam cerita ajaib yang akan mereka kisahkan pada kebarat dan kenalan mereka yang belum sempat mengunjungi kota kami. Mereka akan bercerita bagaimana sebuah kota perlahan- lahan hancur dan tumbuh kembali. Sebuah kota yang akan mengingatkanmu pada yang rapuh, sementara, dan fana. Sebuah kota yang membuat para pelancong berdatangan ingin menyaksikannya.
Bila kau merencanakan liburan akhir pekan dan kau sudah bosan piknik ke kota-kota besar dunia yang megah dan gemerlap—ada baiknya kau berkunjung ke kota kami. Jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan penderitaan kami. Mungkin itu bisa membuatmu sedikit terhibur dan gembira. Berwisatalah ke kota kami. Jangan khawatir, kami pasti akan menyambut kedatanganmu dengan kalungan bunga-air mata…
Yogyakarta, 2006
Mata Mungil yang Menyimpan Dunia
Cerpen Agus Noor
Selalu. Setiap pagi. Setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia selalu melihat bocah itu tengah bermain- main di kolong jalan layang. Kadang berloncatan, seperti menjolok sesuatu. Kadang hanya merunduk jongkok memandangi trotoar, seolah ada yang perlahan tumbuh dari celah conblock.
Karena kaca mobil yang selalu tertutup rapat, Gustaf tak tak bisa mendengarkan teriakan-teriakan bocah itu, saat dia mengibaskan kedua tangannya bagai menghalau sesuatu yang beterbangan. Gustaf hanya melihat mulut bocah itu seperti berteriak dan tertawa-tawa. Kadang Gustaf ingin menurunkan kaca mobil, agar ia bisa mendengar apa yang diteriakkan bocah itu. Tapi Gustaf malas menghadapi puluhan pengemis yang pasti akan menyerbu begitu kaca mobilnya terbuka.
Maka Gustaf hanya memandangi bocah itu dari dalam mobilnya yang merayap pelan dalam kemacetan. Usianya paling 12 tahunan. Rambutnya kusam kecoklatan karena panas matahari. Selalu bercelana pendek kucel. Berkoreng di lutut kirinya. Dia tak banyak beda dengan para anak jalanan yang sepertinya dari hari ke hari makin banyak saja jumlahnya. Hanya saja Gustaf sering merasa ada yang berbeda dari bocah itu. Dan itu kian Gustaf rasakan setiap kali bersitatap dengannya. Seperti ada cahaya yang perlahan berkeredapan dalam mata bocah itu. Sering Gustaf memperlambat laju mobilnya, agar ia bisa berlama-lama menatap sepasang mata itu.
Memandang mata itu, Gustaf seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan. Hingga ia merasa segala di sekeliling bocah itu perlahan-lahan berubah. Tiang listrik dan lampu jalan menjelma menjadi barisan pepohonan rindang. Tak ada keruwetan, karena jalanan telah menjadi sungai dengan gemericik air di sela bebatuan hitam. Jembatan penyeberangan di atas sana menjelma titian bambu yang menghubungkan gedung-gedung yang telah berubah perbukitan hijau. Dari retakan trotoar perlahan tumbuh bunga mawar, akar dedaunan hijau merambat melilit tiang lampu dan pagar pembatas jalan, kerakap tumbuh di dinding penyangga jalan tol. Gustaf terkejut ketika tiba-tiba ia melihat seekor bangau bertengger di atas kotak pos yang kini tampak seperti terbuat dari gula-gula. Air yang jernih dan bening mengalir perlahan, seakan- akan ada mata air yang muncul dari dalam selokan. Kicau burung terdengar dari pohon jambu berbuah lebat yang bagai dicangkok di tiang traffic light.
Gustaf terpesona menyaksikan itu semua. Ia menurunkan kaca mobilnya, menghirup lembab angin yang berembus lembut dari pegunungan. Tapi pada saat itulah ia terkejut oleh bising pekikan klakson mobil-mobil di belakangnya. Beberapa pengendara sepeda motor yang menyalip lewat trotoar melotot ke arahnya. Seorang polisi lalu lintas bergegas mendekatinya. Buru-buru Gustaf menghidupkan mobilnya dan melaju. Gustaf jadi selalu terkenang mata bocah itu. Ia tak pernah menyangka betapa di dunia ini ada mata yang begitu indah. Sejak kecil Gustaf suka pada mata. Itu sebabnya ketika kanak-kanak ia menyukai boneka. Ia menyukai bermacam warna dan bentuk mata boneka-boneka koleksinya. Ia suka menatapnya berlama-lama. Dan itu rupanya membuat Mama cemas—waktu itu Mama takut ia akan jadi homoseks seperti
Oom Ridwan, yang kata Mama, sewaktu kanak-kanak juga menyukai boneka—lantas segera membawanya ke psikolog. Berminggu-minggu mengikuti terapi, ia selalu disuruh menggambar. Dan ia selalu menggambar mata. Sering ia menggambar mata yang bagai liang hitam. Sesekali ia menggambar bunga mawar tumbuh dari dalam mata itu; mata dengan sebilah pisau yang menancap; atau binatang-binatang yang berloncatan dari dalam mata berwarna hijau toska.
Ia senang ketika Oma memuji gambar-gambarnya itu. Oma seperti bisa memahami apa yang ia rasakan. Ia ingat perkataan Oma, saat ia berusia tujuh tahun, ”Mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya….” Sejak itu Gustaf suka memandang mata setiap orang yang dijumpainya. Tapi Papa kerap menghardik, ”Tak sopan menatap mata orang seperti itu!” Papa menyuruhnya agar selalu menundukkan pandang bila berbicara dengan seseorang.
Saat remaja ia tak lagi menyukai boneka, tapi ia suka diam-diam memperhatikan mata orang-orang yang dijumpainya. Kadang—tanpa sadar_ia sering mendapati dirinya tengah memandangi mata seseorang cukup lama, hingga orang itu merasa risi dan cepat-cepat menyingkir. Setiap menatap mata seseorang, Gustaf seperti melihat bermacam keajaiban yang tak terduga. Kadang ia melihat api berkobar dalam mata itu. Kadang ia melihat ribuan kelelawar terbang berhamburan. Sering pula ia melihat lelehan tomat merembes dari sudut mata seseorang yang tengah dipandanginya. Atau dalam mata itu ada bangkai bayi yang terapung-apung, pecahan kaca yang menancap di kornea, kawat berduri yang terjulur panjang, padang gersang ilalang, pusaran kabut kelabu dengan kesedihan dan kesepian yang menggantung.
Di mana-mana Gustaf hanya melihat mata yang keruh menanggung beban hidup. Mata yang penuh kemarahan. Mata yang berkilat licik. Mata yang tertutup jelaga kebencian. Karena itu, Gustaf jadi begitu terkesan dengan sepasang mata bocah itu. Rasanya, itulah mata paling indah yang pernah Gustaf tatap. Begitu bening begitu jernih. Mata yang mungil tapi bagai menyimpan dunia.
Alangkah menyenangkan bila memiliki mata seperti itu. Mata itu membuat dunia jadi terlihat berbeda. Barangkali seperti mata burung seriwang yang bisa menangkap lebih banyak warna. Setiap kali terkenang mata itu, setiap kali itu pula Gustaf kian ingin memilikinya.
Sembari menikmati secangkir cappucino di coffee shop sebuah mal, Gustaf memperhatikan mata orang-orang yang lalu lalang. Mungkin ia akan menemukan mata yang indah, seperti mata bocah itu. Tapi Gustaf tak menemukan mata seperti itu. Membuat Gustaf berpikir, bisa jadi mata bocah itu memang satu-satunya mata paling indah di dunia. Dan ia makin ingin memiliki mata itu. Agar ia bisa memandang semua yang kini dilihatnya dengan berbeda….
Gustaf kini bisa mengerti, kenapa bocah itu terlihat selalu berlarian riang—karena ia tengah berlarian mengejar capung yang hanya bisa dilihat matanya. Bocah itu sering berloncatan—sebab itu tengah menjoloki buah jambu yang terlihat begitu segar di matanya. Mata bocah itu pastilah melihat sekawanan burung gelatik terbang merendah bagai hendak hinggap kepalanya, hingga ia mengibas-kibaskan tangan menghalau agar burung-burung itu kembali terbang. Ketika berjongkok, pastilah bocah itu sedang begitu senang memandangi seekor kumbang tanah yang muncul dari celah conblock. Semua itu hanya mungkin, karena mata mungil indah bocah itu bisa melihat dunia yang berbeda. Atau karena mata mungil itu memang menyimpan sebuah dunia.
Tentulah menyenangkan bila punya mata seperti itu, batin Gustaf. Apa yang kini ia pandangi akan terlihat beda. Ice cream di tangan anak kecil itu mungkin akan meleleh menjadi madu. Pita gadis yang digandeng ibunya itu akan menjadi bunga lilly. Di lengkung selendang sutra yang dikenakan manequin di etalase itu akan terlihat kepompong mungil yang bergeletaran pelan ketika perlahan-lahan retak terbuka dan muncul seekor kupu-kupu. Seekor kepik bersayap merah berbintik hitam tampak merayap di atas meja. Eceng gondok tumbuh di lantai yang digenangi air bening. Elevator itu menjadi tangga yang menuju rumah pohon di mana anak-anak berebutan ingin menaikinya. Ada rimpang menjalar di kaki-kaki kursi, bambu apus tumbuh di dekat pakaian yang dipajang. Cahaya jadi terlihat seperti sulur-sulur benang berjuntaian….
Betapa menyenangkan bila ia bisa menyaksikan itu semua karena ia memiliki mata bocah itu. Bila ia bisa memiliki mata itu, ia akan bisa melihat segalanya dengan berbeda sekaligus akan memiliki mata paling indah di dunia! Mungkin ia bisa menemui orang tua bocah itu baik-baik, menawarinya segepok uang agar mereka mau mendonorkan mata bocah itu buatnya. Atau ia bisa saja merayu bocah itu dengan sekotak cokelat. Apa pun akan Gustaf lakukan agar ia bisa memiliki mata itu. Bila perlu ia menculiknya. Terlalu banyak anak jalanan berkeliaran, dan pastilah tak seorang pun yang peduli bila salah satu dari mereka hilang.
Gustaf tersenyum. Ia sering mendengar cerita soal operasi ganti mata. Ia tinggal datang ke Medical Eyes Centre untuk mengganti matanya dengan mata bocah itu!
Gustaf hanya perlu menghilang sekitar dua bulan untuk menjalani operasi dan perawatan penggantian matanya. Ia ingin ketika ia muncul kembali, semuanya sudah tampak sempurna. Tentu lebih menyenangkan bila tak seorang pun tahu kalau aku baru saja ganti mata, pikirnya. Orang-orang pasti akan terpesona begitu memandangi matanya. Semua orang akan memujinya memiliki mata paling indah yang bagai menyimpan dunia.
Pagi ketika Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya, ia melihat seorang bocah duduk bersimpuh di trotoar dengan tangan terjulur ke arah jalan. Kedua mata bocah itu kosong buta! Gustaf hanya memandangi bocah itu. Ia ingin membuka jendela, dan melemparkan recehan, tapi segera ia urungkan karena merasa percuma.
Ia melangkah melewati lobby perkantoran dengan langkah penuh kegembiraan ketika melihat setiap orang memandang ke arahnya. Beberapa orang malah terlihat melotot tak percaya. Gustaf yakin mereka kagum pada sepasang matanya. Gustaf terkesima memandang sekelilingnya….
Dengan gaya anggun Gustaf menuju lift.
Begitu lift itu tertutup, seorang perempuan yang tadi gemetaran memandangi Gustaf terlihat menghela napas, sambil berbicara kepada temannya.
”Kamu lihat mata tadi?” ”Ya.”
”Persis mata iblis!”
Jakarta, 2006.
Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : 100 Cara Menentukan Unsur Intrinsik Cerpen Dan Novel
Potongan-Potongan Cerita di Kartu Pos
Cerpen Agus Noor
SAYA mendapat beberapa kiriman kartu pos dari Agus Noor. Pada setiap kartu pos yang dikirimnya, ia menuliskan cerita -tepatnya potongan-potongan cerita- tentang Maiya. Berikut inilah cerita yang ditulisnya pada kartu pos-kartu pos itu:
Kartu Pos Pertama & Kedua
MAIYA terpesona melihat kemilau kalung manik-manik itu. Tak pernah Maiya melihat untaian kalung seindah itu. Pastilah dibuat oleh pengrajin yang teliti dan rapi. Ada juga anting-anting, bros dan gelang. Maiya menyangka semua perhiasan itu terbuat dari berlian.
“Ini bukan berlian, Nyonya,” jelas perempuan itu. “Ini manik-manik airmata…”
Maiya memandangi perempuan yang duduk bersimpuh di hadapannya. Mungkin usianya sekitar 35 tahunan. Kulitnya kecoklatan. Bedak tipis sedikit memulas kelelahan di wajahnya. Memakai rok terusan kembang-kembang, terlihat kucel, dan malu-malu. Saat tadi muncul menenteng tas abu-abu, dan tak beralas kaki, Maiya menyangka perempuan itu hendak minta sumbangan.
“Sungguh, Nyonya. Ini butir-butir airmata yang mengeras. Kami menyebutnya biji-biji airmata. Seperti butiran beras kering berjatuhan dari kelopak mata…” Perempuan itu pun terus bercerita, membuat Maiya makin terpesona.
Kartu Pos Ketiga, Empat & Lima
SAAT Maiya datang ke arisan memakai kalung manik-manik itu, semua terbelalak memuji penampilannya yang chic. Maiya melirik ke arah Andien yang muncul menenteng tas koleksi terbaru Hermés -tapi tak seorang pun memujinya. Semua perhatian tersedot kalung manik-manik yang dikenakan Maiya. Membuat Mulan yang memakai bustier dan rok flouncy Louis Vuitton hanya bersandar iri menyaksikan Maiya jadi pusat perhatian. Dengan penuh gaya Maiya bercerita soal kalung manik- manik yang dikenakannya. Dan semua berdecak mendengarnya. “Begitulah yang dikatakan perempuan itu pada saya. Manik-manik ini berasal dari airmata.”
“Jadi itu manik-manik airmata?” tanya Mulan, terdengar sinis. “Jangan-jangan airmata buaya, ha ha…”
Andien ikut tertawa. Yang lain terus menyimak cerita Maiya.
“Lihat saja bentuknya, persis airmata yang menetes. Begitu halus. Bening. Berkilauan… Lebih indah kan ketimbang yang bermerek? Lagi pula gue emang nggak brand minded, kok!” Lalu Maiya melirik Mulan yang beringsut mengambil cocktail.
Dari jauh Andien dan Mulan memandangi Maiya.
“Ngapain juga mereka mau dengerin ceritanya yang nggak masuk akal itu,” cibir Mulan.
“Dia cuma cari perhatian,” ujar Andien. “Gue tahu kok, dia nggak bahagia. Sudah nggak lagi dapat perhatian. Dani mulai selingkuh…”
Mulan hanya mendengus.
Kartu Pos Keenam
DANI hanya tertawa ketika Maiya memperlihatkan kalung manik-manik itu. “Di Tanah Abang juga banyak,” komentarnya pendek, sambil mematut diri di depan kaca, menyemprotkan parfum. Baru dua jam Dani balik ke rumah, kini hendak keluar lagi.
“Ini beda. Lihat deh…”
“Sorry, aku mesti pergi.” Lembut Dani mencium kening Maiya. Maiya ingin menahan. Ingin bercerita, betapa sejak ia punya kalung itu ia selalu mendengar suara tangis yang entah dari mana datangnya. Suara tangis yang bagai merembes dari dalam mimpinya. Tangis yang selalu didengarnya setiap malam, saat ia tidur sendirian. Maiya ingin menceritakan itu semua, tapi Dani sudah tergesa keluar menutup pintu kamar.
Kartu Pos Ketujuh
MOBIL meluncur pelan di bawah gemerlap malam.
“Tadi gue iri ama Maiya. Dia pakai kalung manik-manik. Bagus banget. Katanya terbuat dari airmata.”
“Ha ha.”
“Kamu beliin, ya?” “Nggak.”
“Beli di mana?” “Aku nggak beliin!”
“Kok aku nggak dibeliin?”
“Masa kamu nggak percaya. Aku bener-bener nggak beliin!”
Mulan diam, memandang jalanan yang bermandi cahaya. Segalanya terlihat berkilauan. Kota seperti akuarium raksasa yang digenangi cahaya. Dan ia seperti mengapung kesepian di dalamnya.
“Apa Maiya ngerasa soal kita, ya?”
Dani hanya diam, melirik Mulan yang bersandar di sampingnya. Sementara mobil terus meluncur pelan di bawah gemerlap malam.
Kartu Pos Kedelapan, Sembilan, Sepuluh & Sebelas
SUARA tangis itu mengalir menggenangi mimpinya. Dari segala penjuru, airmata mengalir membanjir menenggelamkan kota. Maiya seperti berada di kota bawah laut. Mobil-mobil menjelma terumbu karang. Orang-orang terlihat seperti ganggang. Suara tangis terus merembes dari gedung-gedung yang penuh lumut. Suara tangis itu juga menjelma gelembung-gelembung air yang keluar dari selokan yang mampet. Maiya menyelam bagai putri duyung dalam dongeng. Ia melihat suaminya terapung seperti gabus. Ia melihat kedua anak kembarnya menjelma ubur-ubur. Airmata telah menenggelamkan kota!
Dan di puncak Monas yang telah tenggelam dalam linangan airmata, Maiya melihat seorang penyair berdiri membaca puisi. “Tanah airmata tanah tumpah dukaku. Mata air airmata kami. Airmata tanah air kami… Di sinilah kami berdiri, menyanyikan airmata kami… Kemana pun melangkah, kalian pijak airmata kami… Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa ke mana pergi. Menyerahlah pada kedalaman airmata kami…”1 Suaranya perlahan meleleh dan mencair, menjelma gelombang airmata.
Saat tergeragap bangun, Maiya mendapati tubuhnya kebah. Suara tangis yang mengapung itu masih didengarnya. Maiya mengira itu tangis anaknya. Tapi ia mendapati Faizi dan Fauzi tertidur tenang di kamarnya. Tangis itu merembes dari balik dinding dan menggenangi ruangan. Maiya tercekat ketika memandangi kotak perhiasan di atas meja, di mana ia menyimpan kalung manik-maniknya. Tangis itu datang dari kotak perhiasan itu, seperti muncul dari gramafon tua.
Gemetar tak percaya, Maiya kembali naik ke tempat tidurnya. Lalu menyadari, tak ada Dani di ranjang. Perlahan ia mulai terisak.
Kartu Pos Keduabelas, Tigabelas & Empatbelas
“HAMPIR setiap malam aku mendengar tangis itu,” Maiya bercerita sambil bersandar ke pundak Andien. “Mungkin itu memang airmata purba yang berabad-abad terpendam dan menjadi fosil. Menjadi batu granit. Lalu mereka membikinnya jadi kalung manik-manik.”
Andien tersenyum, kemudian mengecup bibir Maiya pelan. Berciuman dengan Maiya seperti menikmati mayonnaise yang lembut dan gurih. Andien memandangi wajah Maiya yang mengingatkannya pada roti tawar yang diolesi mentega. Bertahun-tahun diam-diam menjalin hubungan dengan Maiya membuat Andien mengerti, saat ini Maiya membutuhkannya untuk menjadi seorang pendengar. Aroma chamomile yang menguar dalam kamar membuat Maiya perlahan lebih rileks. Andien tahu, Maiya belakangan makin terlihat rapuh. Mungkin karena perkawinannya dengan Dani yang sedang bermasalah, tapi berusaha ditutup-tutupi. Dan soal kalung manik-manik yang selalu dikatakannya terbuat dari airmata itu hanya kompensasi untuk menutupi kegelisahannya.
“Apa kamu juga nggak percaya?” Maiya menggeliat, menatap Andien. “Mungkin itu memang manik-manik airmata. Kenapa tak kau buktikan saja sendiri? Kamu bisa cari alamat perempuan itu.”
Maiya mendekatkan kalung manik-manik itu ke telinga Andien, “Dengerin, deh…”
Andien merinding, ketika ada dingin yang mendesir, dan ia seperti mendengar isak tangis keluar dari kalung manik-manik yang berkilauan itu.
Kartu Pos Kelimabelas & Enambelas
INI perjalanan paling aneh, seperti mencari alamat yang tak ada dalam peta. Jalanan yang becek penuh lubang membuat mobil tak bisa masuk ke perkampungan itu. Bau kayu busuk dan tai kerbau membuat perut mual. Seseorang menunjuk arah yang ditanyakan Maiya dan Andien. Rumah itu reyot nyaris ambruk. Seperti semua rumah di perkampungan ini. Atap-atap rumbia yang melorot terlihat kelabu tertutup debu. Maiya meyakinkan diri, betapa ia tidak memasuki ruang dan waktu yang salah.
Sungguh, Maiya tak pernah menyangka bahwa ada tempat sebegini kumuh dan terbelakang. Ini dunia yang tak pernah ia lihat dalam majalah-majalah life style yang selalu dibacanya.
“Kita masih di Indonesia, kan?”
Andien nyaris tertawa mendengar perkataan Maiya. Tapi ia langsung menutup mulut ketika puluhan anak-anak kurus kumuh berperut buncit memandanginya dengan tatapan nanar.
Kartu Pos Ketujuhbelas, Delapanbelas & Sembilanbelas
MAIYA dan Andien duduk di bale-bale, mendengarkan laki-laki tua itu bercerita. Maiya segera tahu, laki-laki itu adalah yang dituakan di kampung ini.
“Kalian lihat sendiri anak-anak di sini. Kurus karena busung lapar. Bayi-bayi lahir sekarat. Ibu-ibu tak lagi bisa menyusui. Susu mereka kering. Kelaparan mengeringkan semua yang kami miliki. Mengeringkan airmata kami. Sudah lama kami tak bisa lagi memangis. Buat apa menangis? Tak akan ada yang mendengar tangisan kami. Bahkan begitu lahir, bayi-bayi di sini tak lagi menangis. Kami terbiasa menyimpan tangis kami. Membiarkan tangis itu mengeras dalam kepahitan hidup kami. Mungkin karena itulah, perlahan-lahan tangisan kami mengristal jadi butiran airmata. Dan pada saat- saat kami menjadi begitu sedih, butir-butir airmata yang mengeras itu berjatuhan begitu saja dari kelopak mata kami.” Laki-laki tua itu menarik nafas pelan. “Kalian lihat sendiri…”
Maiya melihat ke pojok yang ditunjuk laki-laki tua itu. Di atas dipan tergolek bocah berperut busung. Tangan dan kakinya kurus pengkor. Mulutnya perot. Tulang-tulang iga bertonjolan. Matanya kering. Dan Maiya terpana ketika menyaksikan dari sepasang mata bocah itu keluar berbutir airmata. Seperti biji-biji jagung yang berjatuhan dari sudut kelopaknya yang bengkak.
“Begitulah, kami mengumpulkan butian-butiran airmata kami. Kemudian kami menguntainya jadi bermacam kerajinan dan perhiasan. Dengan menjual manik-manik airmata itu kami bisa bertahan hidup.”
Andien meremas tangan Maiya yang terdiam memandangi butir-butir airmata yang
terus keluar dalam kelopak mata bocah itu. Terdengar bunyi kletik… kletik… ketika butir-butir airmata itu berjatuhan ke dalam baskom yang menampungnya.
Kartu Pos Keduapuluh
MALAM itu Maiya sendirian dalam kamar. Sudah dua hari Dani tak pulang. Rasanya ia ingin menangis. Tapi ia hanya berbaring gelisah di ranjang. Sesekali ia melirik ke meja riasnya, di mana tergeletak kalung manik-manik airmata itu. Ia kini mengerti, mengapa setiap malam ia mendengar suara tangis yang bagai menggenangi kamar. Setiap butir manik-manik airmata itu memang menyimpan tangisan yang ingin didengarkan.
Alangkah lega bila bisa menangis, desah Maiya sembari memejam mendengarkan lagu yang mengalun pelan dari stereo set yang ia putar berulang-ulang. Menangislah bila harus menangis…2 Sudah berapa lamakah ia tak lagi menangis? Mungkinkah bila ia terus menahan tangis, airmatanya juga akan membeku menjadi manik-manik airmata?
Kartu Pos Terakhir
KETIKA Maiya tertidur, ia merasakan ada bebutiran airmata perlahan jatuh bergulir dari pelupuk matanya yang membengkak…
***
TIGA bulan setelah menerima kartu pos terakhir, saya mendapat kiriman paket. Isinya kalung manik-manik yang begitu indah. Pada secarik kertas, Agus Noor menulis: Ini kalung manik-manik airmata Maiya.
Saya meremas surat itu, dan membuangnya. Saya pikir, setelah bercerai dengan Maiya, saya tak akan diganggu hal-hal konyol macam ini. Benarkah ini manik-manik airmata Maiya? Saya pandangi kalung manik-manik itu. Memang bentuknya seperti butiran airmata yang mengeras.
Mulan muncul dari dalam kamar, dan melihat kalung manik-manik yang tengah saya pandangi.
“Apa tuh, Dan?”
“Ehmm…” Saya tersenyum, memeluk pinggang Mulan. “Ini aku beliin kalung buat kamu.”
***
Jakarta, 2006
Sirkus
Cerpen Agus Noor
ROMBONGAN sirkus itu muncul ke kota kami….
Gempita tetabuhan yang menandai kedatangan mereka membuat kami–anak-anak yang lagi asyik bermain jet-skateboard–langsung menghambur menuju gerbang kota. Rombongan sirkus itu muncul dari balik cakrawala. Debu mengepul ketika roda-roda kereta karnaval berderak menuju kota kami. Dari kejauhan panji-panji warna-warni terlihat meliuk-liuk mengikuti musik yang membahana. Dan kami berteriak-teriak gembira, “Sirkus! Sirkus! Horeee!!!”
Sungguh beruntung kami bisa melihat rombongan sirkus itu. Mereka seperti nasib baik yang tak bisa diduga atau diharap-harapkan kedatangannya. Rombongan sirkus itu akan datang ke satu kota bila memang mereka ingin datang, menggelar pertunjukan semalam, kemudian segera melanjutkan perjalanan. Rombongan sirkus itu layaknya kafilah pengembara yang terus-menerus mengelilingi dunia, melintasi benua demi benua, menyeberangi lautan dan hutan-hutan, menembus waktu entah sejak kapan.
Kisah-kisah ajaib tentang mereka sering kami dengar, serupa dongeng yang melambungkan fantasi kami. Banyak yang percaya, sirkus itu ada sejak mula sabda. Merekalah arak-arakan sirkus pertama yang mengiringi perjalanan Adam dan Eva dari firdaus ke dunia. Mereka legenda yang terus hidup dari zaman ke zaman. Ada yang percaya. Ada yang tidak. Karena memang tak setiap orang pernah melihatnya. Sirkus itu tak akan mungkin kau temukan meskipun kau telah tanpa lelah terus memburunya hingga seluruh ceruk semesta. Bukan kau yang berhasil menemukan rombongan sirkus itu. Tapi merekalah yang mendatangimu. Dan itulah keberuntungan. Merekalah sirkus gaib berkereta nasib. Kau hanya dapat berharap diberkahi bintang terang untuk bisa melihatnya. Banyak orang hanya bisa mendengar gema gempita suara kedatangan mereka melintasi kota, tapi tak bisa melihat wujudnya. Orang-orang yang tak diberkati keberuntungan itu hanya mendengar suara arak-arakan mengapung di udara yang makin lama makin sayup menjauh….
Beruntunglah siapa pun yang dikaruniai kesempatan menyaksikan bermacam atraksi dan keajaiban sirkus itu. Menyaksikan para hobbit bermain bola api melintasi tali, centaur dan minotour, mumi Tutankhamun yang akan meramal nasibmu dengan kartu tarot; peri, Orc, Gollum, unta yang berjalan menembus lubang jarum; mambang, kadal terbang Kuehneosaurus – bermacam makhluk yang kau kira hanya bisa kau temui dalam dongeng.
Kami belum pernah melihat sirkus itu. Tapi kami yakin kalau yang muncul dari balik cakrawala itu memang rombongan sirkus yang melegenda itu. Kami bisa mengenali dari riang rampak rebana dan lengking nafiri yang menyertai kemunculannya. Gempita tetabuhan itu bagai muncul dari kenangan kami yang paling purba.
Rasanya, di kota kami, hanya satu orang yang pernah melihat sirkus itu. Peter Tua yang tak henti bercerita, bagaimana lima tahun lalu ketika ia berada di New Orleans– sehari setelah kota itu dilanda badai Katrina untuk kesekian kalinya–ia menyaksikan rombongan sirkus itu muncul dan waktu seperti beringsut mundur: mendadak semua benda porak-poranda yang dilintasi rombongan sirkus itu langsung untuk kembali. Reruntuh puing rumah perlahan saling rekat, gedung-gedung yang roboh kembali tegak, debu lengket pada dinding, lumpur surut ke sungai, kaca-kaca pecah jadi utuh seperti sediakala. Peter Tua selalu menceritakan peristiwa itu dengan mata menyala- nyala.
Dan kini, betapa beruntungnya, rombongan sirkus itu singgah di kota kami.
***
SEKETIKA, kami–seluruh warga Oklahoma–berjajar sepanjang jalan mengelu-elukan rombongan sirkus yang bergerak pelan memasuki kota. Kami menyaksikan selusin kurcaci menari-nari di atas kereta karavan, singa berambut api yang rebahan setengah mengantuk di kandang. Dan itu…, lihat! Dumbledore! Memakai jubah dan topi penyihir warna ungu gemerlapan, berkacamata bulan separuh, tersenyum melambai- lambaikan tangan. Konfeti serangga mendadak berhamburan. Semua orang bersorak riang. Karnaval keajaiban terus mengalir. Badut-badut. Penari ular. Putri duyung berkalung mutiara air mata. Astaga, kami bahkan menyaksikan Hippogriff, unicorn, Aragog, burung phoenix yang lahir kembali dari abu tubuhnya, beberapa ekor pixie mungil, Dementor yang telah dijinakkan, serimbun perdu wolfsbane yang terus melolong–lolong, bola Bludger, sapu terbang Nimbus–semua yang bertahun lampau hanya bisa dibaca di buku cerita klasik Harry Potter.
Kemudian kami melihat raksasa troll berkepala empat, yang tiap kepala menghadap ke satu penjuru mata angin, beruar-uar sambil memukuli canang, “Saksikan! Keajaiban manusia terbang! Grrhhhhh Terbang! Manusia terbang! Manusia terbang! Saksikan!
Grrhhhh…. “
Kami bersorak. Kami bersorai.
***
INILAH malam paling menakjubkan dalam hidup kami yang fana. Kami memenuhi tenda raksasa, yang sepertinya tiba-tiba sudah berdiri begitu saja di tengah kota. Keriangan mengalir seperti cahaya yang menjelma sungai fantasi. Bermacam akrobat atraksi pertunjukan membuat kami seperti tersihir, seakan-akan kebahagiaan ini tak akan pernah berakhir. Lima kuda sembrani berputaran. Kembang api naga. Kungfu pisau terbang. Bayi bersayap jelita. Kami begitu diluapi ketakjuban dan berharap semoga semua keajaiban yang kami saksikan tak akan pernah berakhir, ketika seorang gipsi tua tukang cerita muncul ke tengah arena.
“Saya akan menghantar Anda ke pertunjukan utama. Keajaiban yang kalian nanti- nantikan. Tapi, terlebih dulu, izinkan hamba bercerita.”
Ia merentangkan tangan, hingga semua terdiam.
“Dari zaman ke zaman sirkus kami memperlihatkan bermacam keajaiban, yang hamba harap, bisa memberi sedikit pencerahan. Apalah guna keajaiban, bila semua itu tidak membuat Anda jadi makin menyadari betapa mulia dan berharganya hidup ini. Seperti yang terjadi pada manusia terbang ini. Kami menemukannya bertahun lalu, selepas melintas Samudra Hindia. Kami tiba di Flores, Nusa Tenggara. Dan kami melihatnya, makhluk-makhluk malang itu! Melayang-layang di antara reruncing stalaktit gua kapur Liang Bua. Kami mula-mula menduga, itu kalong raksasa.” Gipsi tua itu sejenak menarik nafas dalam-dalam, sampai kemudian ia menghembuskannya sembari berteriak, “Ternyata manusia!”
“Aku tahu!” seorang penonton berteriak memotong, “Itu pasti Homo Floresiensis.”
Gipsi tua itu tersenyum sabar, “Ini spesies Homo sapiens yang lebih modern. Kita tahu, sampai saat ini tak ada satu manusia modern pun yang bisa terbang. Kecuali dengan bantuan mesin. Namun, kali ini Anda akan menyaksikan sendiri manusia- manusia yang bisa terbang melayang-layang!! Selamat menyaksikan “
Musik membahana. Cahaya tumpah ke arena. Dari kotak-kotak yang mulai terbuka perlahan bermunculan tubuh-tubuh yang begitu ringan, seperti ular keluar dari keranjang. Tubuh-tubuh itu melenting ringan, mengapung mengambang seperti balon gas yang membumbung. Di pinggang mereka ada sabuk berkait yang diikat sejuntai tali, di mana masing-masing tali itu dipegangi satu orang kate bertopi kerucut. Sesekali ada yang membumbung sampai nempel di langit-langit tenda, dan segera orang kate yang memegangi tali itu menariknya turun. Orang-orang kate itu berlarian berputar- putar, persis kanak-kanak yang gembira dengan balon warna-warni di tangan mereka.
“Kami terpaksa mengikat mereka. Bila tidak, mereka akan membumbung terusss ,
lenyap ke langit. Mungkin ke surga. Sudah jutaan yang lenyap, seperti generasi yang menguap. Yang tersisa memilih tinggal di gua-gua. Di situlah, kami menemukan mereka. ” Gipsi tua itu terus bercerita.
Kami terpana didera kengerian dan perasaan hampa. Ada yang ganjil dari orang-orang yang melayang-layang itu. Mulut mereka kosong setengah terbuka. Kulit cokelat- kusam mereka terlihat seperti buah sawo matang yang mulai membusuk. Sampai kami menyadari, sesungguhnya mereka tak bisa terbang, tapi hanya melayang-layang. Gerangan apakah yang membuat mereka jadi seperti itu? Mata mereka penuh kesedihan. Ini keajaiban ataukah kesengsaraan? Lidah kami pahit, dan kami mulai terisak. Di barisan depan, gadis-gadis menunduk tak tega. Seorang ibu dengan gemetar memeluk anaknya. Nenek bergaun hijau terisak sebak. Seperti ada kesenduan yang pelan-pelan menangkupi kami. Ya, kami, kami disesah kesedihan yang sama. Kami semua, semua…juga aku! Aku yang turut menyaksikan pertunjukan itu dan menceritakan semua ini kepadamu.
Aku melirik Mom dan Dad, yang duduk di sebelahku. Mom mengatup dan memejam. Dad terlihat menahan tangis…
***
ROMBONGAN sirkus itu telah pergi. Mungkin sekarang di Montana atau Wisconsin atau Toronto atau terus melintasi Teluk Hudson, Laut Labrador, Green Land sampai Kutub Utara. Tapi aku selalu terkenang sirkus itu. Teringat manusia-manusia terbang itu: kulit sawo matangnya, hidungnya yang kecil. Mirip aku.
Aku hanya diam bila kini teman-teman sekolah sering meledekku. “Hai, lihat itu keturunan manusia terbang”, dan serentak mereka tertawa bila aku melintas. Hanya karena kulitku cokelat, dan rambutku tak pirang seperti mereka. Aku tak marah, hanya merasa geli dan agak jijik dipersamakan seperti itu. Rasanya tubuhku jadi seperti dihuni makhluk ganjil. Mom menegurku, karena belakangan sering melamun. Kubilang, aku baik-baik saja. Sampai suatu malam Dad mengajakku rebahan di atap loteng. Agak lama kami hanya diam memandangi bintang-bintang
“Kamu memikirkan manusia-manusia terbang itu, kan?” Dad menepuk bahuku. Aku terus diam.
“Baiklah, Nak. Sudah saatnya kuceritakan rahasia ini padamu. Mereka berasal dari negeri yang telah collapse puluhan tahun lalu. Negeri yang terus-menerus dilanda kerusuhan. karena para pemimpinnya selalu bertengkar. Kerusuhan sepertinya sengaja dibudidayakan. Perang saudara meletus. Flu burung mengganas. Rakyat kelaparan sengsara. Sementara minyak mahal, dan langka. Orang-orang harus antre dan berkelahi untuk mendapatkan minyak, juga air bersih dan beras. Pengangguran tak bisa diatasi. Bangkai terbengkelai. Lebih dari 23 juta balita menderita kekurangan gizi. Terserang folio, lumpuh layuh, busung lapar. Menderita marasmik kuasiorkor akut. Otak balita-balita itu menyusut. Terkorak mereka kopong. Perut busung. Bahkan tak ada akar yang bisa mereka makan. Sebab tanah, hutan, sungai dan teluk rusak parah tercemar limbah. Karena tak ada lagi yang bisa dimakan, orang-orang kelaparan itu pun mulai belajar menyantap angin. Bertahun-tahun, paru-paru dan perut mereka hanya berisi angin hingga tubuh mereka makin mengembung dan terus mengembung, seperti balon yang dipompa. Jadi begitulah, Nak. Seperti yang kau lihat di sirkus, mereka sesungguhnya tak bisa terbang, tapi melayang-layang karena kepala dan tubuh mereka kosong “
Napas Dad terdengar merendah. Aku seperti merasa ada yang perlahan pecah dan tumpah.
“By the way…, ada juga penduduk negeri itu yang bisa menyelamatkan diri. Yakni sebagian kecil mereka yang pergi mencari jazirah baru dengan menjadi manusia perahu, seperti orang-orang Vietnam. Terombang-ambing di samudra, dan terdampar menjadi imigran. Salah satu dari para imigran itu, tak lain ialah kakekmu. Kamu wangsa pendatang, Nak. That’s why your skin not fair and your hair not blond like your friends that mock you. “
Dad terisak. Aku menatap langit. Berharap melihat tubuh-tubuh gembung busung itu melayang di antara bintang-bintang. Semoga, seperti kata gipsi tua itu, mereka memang menuju surga….